Sejarah Pergerakan Pemuda - Berdirinya GMKI

A.1. Gerakan Mahasiswa 1908
Lahirnya generasi pertama lapisan pemuda berpendidikan modern, sebenarnya bukanlah produk sosial yang murni berasal dari rakyat Indonesia. Kehadiran mereka merupakan produk situasi atau didorong oleh perubahan sikap politik pemerintahan kolonial Belanda terhadap negeri ini. Dalam masa yang penuh tantangan dihadapkan dengan suasana kolonialisme, realitas politik berupa berlangsungnya proses pembodohan dan penindasan secara struktural yang dilakukan Belanda, berkat kemajuan pendidikan yang berhasil mereka raih berimplikasi pada peningkatan tingkat kesadaran politik, para pelajar dan mahasiswa merasakan sebagai golongan yang paling beruntung dalam pendidikan sehingga muncul tanggung jawab untuk mengemansipasi bangsa Indonesia.
Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya.
Dalam 5 tahun permulaan BU sebagai perkumpulan, tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan, mempunyai kedudukan monopoli dan oleh karena itu BU maju pesat, tercatat akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan lk.10.000 anggota. Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan perkumpulan : Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan.
Disamping itu, pada tahun yang sama dengan berdirinya BU oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, dibentuk pula Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama baru menjadi Perhimpunan Indonesia,tahun 1925.
Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain,seperti: Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam,dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) yang berhaluan Marxis, dll menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan BU karena banyak orang kemudian memandang BU terlalu lembek oleh karena hanya menuju “kemajuan yang selaras” dan /atau terlalu sempit keanggotaannya (hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa) meninggalkan BU Oleh karena cita-cita dan pemandangan umum berubah ke arah politik, BU juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik.
Kehadiran Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia : generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.
A.2. Gerakan Mahasiswa 1928
Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925.
Suatu gejala yang tampak pada gerakan mahasiswa dalam pergolakan politik di masa kolonial hingga menjelang era kemerdekaan adalah maraknya pertumbuhan kelompok-kelompok studi sebagai wadah artikulatif di kalangan pelajar dan mahasiswa. Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, menyusul kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), prototipe organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, kelompok Studi St. Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereninging (CSV) bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club (SIS) bagi mahasiswa Islam pada tahun 1930-an.
Lahirnya pilihan pengorganisasian diri melalui kelompok-kelompok studi tersebut, dipengaruhi kondisi tertentu dengan beberapa pertimbangan rasional yang melatari suasana politis saat itu. Pertama, banyak pemuda yang merasa tidak dapat menyesuaikan diri, bahkan tidak sepaham dan kecewa dengan organisasi-organisasi politik yang ada. Sebagian besar pemuda saat itu, misalnya menolak ideologi Komunis (PKI) maka mereka mencoba bergabung dengan kekuatan organisasi lain seperti Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo. Namun, karena kecewa tidak dapat melakukan perubahan dari dalam dan melalui program kelompok-kelompok pergerakan dan organisasi politik tersebut, maka mereka kemudian melakukan pencarian model gerakan baru yang lebih representatif.
Kedua, kelompok studi dianggap sebagai media alternatif yang paling memungkinkan bagi kaum terpelajar dan mahasiswa untuk mengkonsolidasikan potensi kekuatan mereka secara lebih bebas pada masa itu, dimana kekuasaan kolonialisme sudah mulai represif terhadap pembentukan organisasi-organisasi massa maupun politik.
Ketiga, karena melalui kelompok studi pergaulan di antara para mahasiswa tidak dibatasi sekat-sekat kedaerahan, kesukuan,dan keagamaan yang mungkin memperlemah perjuangan mahasiswa.
Ketika itu, disamping organisasi politik memang terdapat beberapa wadah perjuangan pemuda yang bersifat keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan yang tumbuh subur, seperti Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, dan lain-lain.
Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia: generasi 1928. Maka, tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi ini adalah menggalang kesatuan pemuda, yang secara tegas dijawab dengan tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober1928, dimotori oleh PPPI.
A.3. Gerakan Mahasiswa 1945
Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk secara terbuka mentransformasikan eksistensi wadah mereka menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).
Seiring dengan keluarnya Belanda dari tanah air, perjuangan kalangan pelajar dan mahasiswa semakin jelas arahnya pada upaya mempersiapkan lahirnya negara Indonesia di masa pendudukan Jepang. Namun demikian, masih ada perbedaan strategi dalam menghadapi penjajah, yaitu antara kelompok radikal yang anti Jepang dan memilih perjuangan bawah tanah di satu pihak, dan kelompok yang memilih jalur diplomasi namun menunggu peluang tindakan antisipasi politik di pihak lain. Meskipun berbeda kedua strategi tersebut, pada prinsipnya bertujuan sama : Indonesia Merdeka !
Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan.
Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa.
Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok “bawah tanah” yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok itu dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antar generasi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan pemuda (yang cenderung militan dan non kompromis) menuntut peluang tersebut segera dimanfaatkan, tetapi generasi tua seperti Soekarno dan Hatta cenderung lebih memperhitungkan situasi secara realistis. Tetapi akhirnya kedua tokoh proklamator itu mengabulkan keinginan pemuda, dan memproklamasikan negara Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan saat itu, maka sekaligus menandai lahirnya generasi 1945 dalam sejarah Indonesia.
A.4. Gerakan Mahasiswa 1966
Suasana Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan hingga Demokrasi Parlementer,lebih diwarnai perjuangan partai-partai politik yang saling bertarung berebut kekuasaan. Pada saat yang sama mahasiswa sendiri lebih melihat diri mereka sendiri sebagai The Future Man ; artinya, sebagai calon elit yang akan mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan yang akan dibangun. Dalam periode ini, pola kegiatan mahasiswa kebanyakan diisi dengan kegiatan sosial seperti piknik, olahraga, pers, dan klub belajar. Hal ini juga sebagian karena dipengaruhi oleh munculnya orientasi pemikiran untuk kembali ke kampus dan slogan kebebasan akademik yang membius semangat mahasiswa saat itu. Hanya sedikit perhatian diantara mereka untuk memikirkan masalah-masalah politik.
Namun demikian, di satu sisi masa itu juga ditandai dengan mulai aktifnya organisasi mahasiswa yang tumbuh berafiliasi partai politik dan aktivis mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik nasional yang berperan dalam sistem politik.
Di sisi lain, ada pula perkembangan menarik yang terjadi dengan tumbuhnya aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947.
Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan lebih bersifat underbouw partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.
Diantara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI mendapatkan suasana menggembirakan setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. Sebagai wujud kegembiraan namun sekaligus kepongahan, CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha mempengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 1961. Persaingan ini mencapai puncak nantinya tatkala terjadi G30S/PKI.
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), seiring dengan upaya pemerintahan Soekarno untuk mengubur partai-partai, maka kebanyakan organisasi mahasiswa pun membebaskan diri dari afiliasi partai dan tampil sebagai aktor kekuatan independen, sebagai kekuatan moral maupun politik yang nyata.
Tragedi nasional pemberontakan G30S/PKI dan kepemimpinan nasional yang mulai otoriter akhirnya menyebabkan Demokrasi Terpimpin mengalami keruntuhan.
Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.
Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain.
A.5. Gerakan Mahasiswa 1974
Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer yang berposisi sebagai pendukung kemapanan.
Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru.namun meskipun demikian pada umumnya kepercayaan terhadap rezim yang berkuasa tetap ada.
Tetapi, kesabaran mahasiswa mulai menuju titik batasnya setelah penantian akan terkabulnya cita-citanya perubahan yang dijanjikan tidak mendapatkan respon yang sewajarnya. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan “Mahasiswa Menggugat”yang dimotori Arif Budiman,dkk yang progaram utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi.
Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK). Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat.
Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.
Akibat dari permainan rekayasa dan kebijakan kooptasi tersebut, muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung N, Asmara Nababan,dkk.
Dalam tahun 1971, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri.
Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya peristiwa Malari tahun 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta mngajukan isu ”ganyang korupsi” sebagai salah satu tuntutan “Tritura Baru” disamping dua tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya.
Terlepas dari semua distorsi mengenai kisah gerakan mahasiswa 1974,antara lain: tidak adanya perubahan monumental yang ditinggalkan, gerakan mahasiswa yang ditunggangi, konflik dan konspirasi elit di pusat kekuasaan versi Jenderal Sumitro versus Ali Moertopo, dll bagaimana pun harus diakui bahwa perjuangan mahasiswa 1974 telah menjadi sebuah episode yang bersejarah.
A.6. Gerakan Mahasiswa 1978
Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes tetap ada namun aksi-aksi itu pada umumnya tidak lagi gaung yang berarti.
Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif.Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai burning isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat “lokal”.
Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan “berkampanye”di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian , upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa.
Mahasiswa bukan tidak memahami ataupun menyadari berbagai risiko buruk yang bakal dialami akibat gerakan protes mereka. Justru karena itulah, untuk menjaga agar dampak gerakan tidak mengulangi kembali malapetaka 1974, mahasiswa mempertahankan gerakan aksi mereka sebagai gerakan moral semata. Artinya, bahwa gerakan mereka lebih menonjolkan perannya sebagai kekuatan moral dan kontrol kritis terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan, dan bukan sebagai aksi yang berorientasi politik praktis, serta menghindarkan pengaruh vested interest kelompok politik tertentu yang ingin memperalat atau “mengendarai” gerakan mahasiswa.
Pada titik ini ada yang menarik untuk dicatat yaitu terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus itu; disamping penyebabnya adalah karena mahasiswa dianggap telah melakukan “pembangkangan politik”, penyebab lain sebenarnya adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus.
Jadi, karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk mennghindari seperti tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer,malahan dengan cara yang brutal.
Akhir cerita, Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional.
A.7. Gerakan Mahasiswa di Era NKK/BKK
Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa.
Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik,dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul pemberlakuan konsep NKK,pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan,pengarahan,dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.
Dengan konsep NKK/BKK ini, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian Ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis,sementara posisi rezim semakin kuat.
Sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus, di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi yang dianggap mungkin tidak tersentuh kekuasaan refresif penguasa. Kenyataannya, kelompok studi lebih berfungsi sebagai information actions dengan tujuan the distribution of critical information bagi mahasiswa. Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa.
Perbedaan kedua bentuk wadah ini adalah : jika kelompok studi merupakan bentuk pelarian dari kepengapan kampus dengan ciri gerakannya yang bersifat teoritis, maka LSM menjadi tempat pelarian mahasiswa yang memilih jalur praktis.
Dalam perkembangan berikutnya bermunculan pula berbagai wadah-wadah lain berupa komite-komite aksi untuk merawat kesadaran kritis mahasiswa.
Beberapa kasus “lokal” yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah waduk Kedung Ombo, Kacapiring, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB, dsb.
Timbul beberapa pertanyaan mengapa gerakan mahasiswa umumnya hanya mengusung agenda isu lokal dan cenderung marjinal ? mungkin jawabannya adalah :
1) Ketidakberanian untuk menyentuh masalah yang dinilai terlalu sensitif,dan bebannya berat secara politis.
2) Ketidaksanggupan menangkap dan mengungkapkan masalah-masalah fundamental yang lebih signifikan terutama yang bersifat politik nasional sebagai burning issue.
3) Strategi mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi struktural sistem politik Orde Baru yang terlalu mudah bertindak represif.
Jawaban-jawaban tersebut sangat terbuka untuk diperdebatkan, tetapi ada efek lain yang tampaknya harus diperhitungkan,bahwa justru dengan kecenderungan mengangkat isu-isu lokal dan bergerak di wilayah pinggiran itu, disadari atau tidak mahasiswa telah melakukan revitalisasi orientasi model pendekatan dengan membangkitkan kesadaran dan kepercayaan diri rakyat agar mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak individu dan sosialnya.
A.8. Gerakan mahasiswa 1990
Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menamggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.
Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini dalam eksperimentasi demokrasi. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.
Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT, menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa ditahun 1990-an.
A.9. Gerakan Mahasiswa 1998
Lahirnya gerakan mahasiswa 1998 dengan segala keberhasilannya meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru, bagaimanapun merupakan akibat dari akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan politik yang telah bergejolak selama puluhan tahun dan akhirnya “meledak”.
Secara obyektif situasi pada saat itu, sangat kondusif bagi gerakan mahasiswa berperan sebagai agen perubahan. Krisis legitimasi politik yang sudah diambang batas, justru terjadi bersamaan dengan datangnya badai krisis moneter di berbagai sektor. Di sisi lain secara subyektif, gerakan mahasiswa 1998 telah belajar banyak dari gerakan 1966 dengan mengubah pola gerakan dari kekuatan ekslusif ke inklusif dan menjadi bagian dari kekuatan rakyat,
Sasaran dari tuntutan “Reformasi” gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok lain yang beroposisi terhadap rezim Orde Baru, antara lain adalah perubahan kepemimpinan nasional. Soeharto harus diruntuhkan dari kekuasaan, tidak akan ada reformasi selama Soeharto masih berkuasa. Namun demikian, kenyataan menunjukkan suara-suara kritis yang menuntut perubahan, tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkan dari rezim yang berkuasa, terlebih oleh Golongan Karya (Golkar) yang dengan enteng mencalonkan kembali Soeharto. Menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1998, dari kalangan tokoh-tokoh kritis mengajukan calon alternatif Presiden maupun Wakil Presiden, antara lain: Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Emil Salim.
Kenyataan menunjukkan, calon-calon tandingan versi masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dari kekuatan politik di MPR, Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. Aksi-aksi mahasiswa yang marak mengajukan protes dan keprihatinan, seolah-olah dianggap angin lalu, sedangkan hasil-hasil dialog dengan berbagai fraksi menuntut agenda Reformasi hanya “ditampung” dalam artian kasar = ditolak.
Berbagai kontroversi kemudian timbul dimasyarakat, berkenaan dengan pengalihan kekuasaan ini. Pertama, pandangan yang melihat hal itu sebagai proses inkonstitusional dan sebaliknya pandangan kedua, yang menganggapnya sudah konstitusional. Sikap ABRI terhadap proses peralihan ini secara formal adalah mendukung, lalu bagaiman dengan mahasiswa ?
Menyambut turunnya Soeharto, sejenak mahasiswa benar-benar diliputi kegembiraan. Perjuangan mereka satu langkah telah berhasil,tetapi kemudian timbul keretakan di antara kelompok-kelompok mahasiswa mengenai sikap mahasiswa terhadap peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Berhadapan dengan peristiwa peralihan ini mahasiswa tidak siap, mereka hanya dipersatukan oleh isu utama perlunya Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri. Soal yang terjadi kemudian, agaknya jauh dari antisipasi mahasiswa dan pro reformasi.
Tetapi bagaimanapun, mahasiswa 1998 melalui perjuangannya telah memberikan sesuatu hal yang monumental bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan tatanan kenegaraan yang lebih baik di masa depan.
Satu hal yang harus diingat, Reformasi Total merupakan sebuah proses yang tidak sekali jadi, tetapi membutuhkan waktu dan political will yang sungguh-sungguh dari pemegang kekuasaan. Karena itu, kontrol kritis dan tekanan politik dari mahasiswa harus tetap ada di masa sekarang dan akan datang.
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
B.1. Sejarah Berdirinya GMKI
Berdirinya CSV tidak terpisahkan dengan peranan Ir. C.L Van Doorn, seorang ahli kehutanan yang mempelajari aspek sosial dan ekonomi khususnya ilmu pertanian dan kemudian memperoleh doktor di bidang ekonomi serta sarjana di bidang teologi.
Dengan adanya mahasiswa di Indonesia dan bersamaan dengan berdirinya School tot Opleiding van Indishe Artsen (STOVIA) tahun 1910-1924 di Batavia. Selain itu, berdiri juga Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS) di Surabaya (1913), Sekolah Teknik di Bandung (1920), Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor (1914) dan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta (1924). Pada tahun 1924 terbentuklah Batavia CSV dan inilah cabang CSV yang pertama.
Kurun waktu 1925-1927 para mahasiswa di Surabaya yang tergabung dalam Jong Indie aktif melakukan penelaahan Alkitab. Kelompok ini bersama Batavia CSV mengadakan Konferensi di Kaliurang pada bulan Desember 1932. Pembicara-pembicara utama kegiatan tersebut adalah Dr. J. Leimena, Ir. C.L van Doorn dan Dr. Hendrik Kraemer.
Jumlah anggota CSV op Java dalam kurun waktu 1930-an sekitar 90 orang. Cabang-cabangnya baru ada di kota-kota perguruan tinggi di Jawa (Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya). Walaupun kecil dan lemah namun keberadaan CSV op Java telah berhasil meletakkan dasar bagi pembinaan mahasiswa Kristen yang akan dilanjutkan GMKI di kemudian hari.
Sejumlah mahasiswa kedokteran dan hukum di Jakarta memutuskan untuk membentuk suatu organisasi mahasiswa Kristen. Organisasi itu untuk menggantikan CSV op Java yang sudah tidak ada. Dalam pertemuan di STT Jakarta tahun 1945, dibentuk Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) dengan maksud keberadaannya sebagai Pengurus Pusat PMKI. Dengan demikian Dr. J. Leimena dipilih sebagai Ketua Umum dan Dr. O.E Engelen sebagai Sekretaris Jenderal. Tetapi karena Leimena sibuk dengan tugas-tugas sebagai Menteri Muda Kesehatan, tugas-tugasnya diserahkan kepada Dr. Engelen.
Kegiatan-kegiatan PMKI tidak jauh berbeda dengan CSV op Java dengan Penelahaan Alkitab salah satu inti kegiatannya. Keanggotaan PMKI sebagian besar adalah mahasiswa yang memihak pada perjuangan kemerdekaan. Terbentuklah PMKI di Bandung, Bogor, Surabaya dan Yogyakarta (setelah UGM berdiri) segera menyusul.
Tak lama setelah PMKI lahir, awal tahun 1946 muncul organisasi baru dengan menggunakan CSV di Bogor, Bandung dan Surabaya dengan “CSV yang baru” dan tidak menjadi tandingan PMKI. Kesamaan kedua organisasi ini adalah merealisasikan persekutuan iman dalam Yesus Kristus dan menjadi saksi Kristus dalam dunia mahasiswa.
Masuknya Jepang ke Indonesia mengakhiri eksistensi CSV op Java secara struktural dan organisatoris. Pemerintah pendudukan Jepang melarang sama semua kegiatan-kegiatan organisasi yang dibentuk pada jaman Belanda. Secara prakatis CSV op Java tidak ada lagi sejak tahun 1942. Sepanjang sejarahnya, CSV op Java dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. J. Leimena (1932-1936) serta Mr. Khouw (1936-1939). Sedangkan sekretaris (full time) dijalankan Ir. C.L Van Doorn (1932-1936).
Dengan berakhirnya pertikaian Indonesia dengan Belanda, tahun 1949 berakhir pula “pertentangan” antara PMKI dengan CSV baru tersebut. Tanggal 9 Februari 1950 di kediaman Dr. J. Leimena di Jl. Teuku Umar No. 36 Jakarta, wakil-wakil PMKI dan CSV baru hadir dalam pertemuan tersebut. Maka lahirlah kesepakatan yang menyatakan bahwa PMKI dan CSV baru untuk meleburkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan mengangkat Dr. J. Leimena sebagai Ketua Umum hingga diadakan kongres. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan sangat penting dan suatu moment awal perjuangan mahasiswa Kristen yang tergabung dalam GMKI maka pada kesempatan itu Dr. J. Leimena menyampaikan pesan penting yang mengatakan:
“Tindakan ini adalah suatu tindakan historis bagi dunia mahasiswa umumnya dan masyarakat Kristen pada khususnya. GMKI menjadilah pelopor dari semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakukan di Indonesia. GMKI menjadilah suatu pusat sekolah latihan (leershool) dari orang-orang yang mau bertanggungjawab atas segala sesuatu yang mengenai kepentingan dan kebaikan negara dan bangsa Indonesia. GMKI bukanlah merupakan Gesellschaft, melainkan ia adalah suatu Gemeinschaft, persekutuan dalam Kristus Tuhannya. Dengan demikian ia berakar baik dalam gereja, maupun dalam Nusa dan Bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari iman dan roh, ia berdiri di tengah dua proklamasi: Proklamasi Kemerdekaan Nasional dan Proklamasi Tuhan Yesus Kristus dengan Injilnya, ialah Injil Kehidupan, Kematian dan Kebangkitan”
B.2. Biografi Pendiri GMKI
Dr. Johannes Leimena (Ambon, 6 Maret 1905 - Jakarta, 29 Maret 1977) adalah seorang tokoh politik Indonesia. Leimena menjabat dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak masa Kabinet Sjahrir II (1946) hingga Kabinet Dwikora II (1966), baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, maupun Wakil Menteri Pertama. Selain menjadi Menteri Kesehatan Indonesia yang pertama, Leimena juga menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia yang paling lama (selama 21 tahun) dari 1945-1966. Selain itu, Leimena juga seorang Laksamana Madya (Tituler) di TNI Angkatan Laut.
Leimena menyelesaikan pendidikan kedokterannya di STOVIA, Surabaya (1930), dilanjutkan di Geneeskunde Hogeschool/GHS (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1939. Ia juga salah seorang pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Pada tahun 1914, Leimena hijrah ke Batavia (Jakarta). Di Batavia ia meneruskan studinya ke ELS (Europeesch Lagere School), namun hanya beberapa bulan saja lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang). Dari sini J. Leimena melanjutkan ke MULO Kristen, kemudian ke STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen).
Dengan keaktifannya di Jong Ambon, Leimena ikut mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Perhatian Leimena pada pergerakan nasional kebangsaan berkembang sejak pertengahan tahun 1920-an.
Keprihatinan Leimena atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa, merupakan hal utama yang mendorong niatnya untuk aktif pada "Gerakan Oikumene". Tahun 1926, Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Setelah lulus studi kedokteran STOVIA, Leimena terus mengikuti perkembangan CSV yang didirikannya saat ia duduk di tahun ke 4 di bangku kuliah. CSV merupakan cikal bakal berdirinya GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) tahun 1950.
Tahun 1945 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terbentuk dan pada tahun 1950 Leimena terpilih sebagai ketua umum dan memegang jabatan ini hingga tahun 1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga di tahun 1950. Di lembaga ini Leimena terpilih sebagai wakil ketua yang membidangi komisi gereja dan negara.
J. Leimena mulai bekerja sebagai dokter sejak tahun 1930. Pertama kali diangkat sebagai dokter pemerintah di "CBZ Batavia" (kini RS Cipto Mangunkusumo). Tak lama di sini ia ditugaskan di Karesidenan Kedu saat Gunung Merapi meletus. Setelah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Di rumah sakit ini ia bertugas dari tahun 1931 sampai 1941.
Ketika Orde Baru berkuasa, Leimena mengundurkan diri dari tugasnya sebagai menteri, namun ia masih dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) hingga tahun 1973. Usai aktif di DPA, ia kembali melibatkan diri di lembaga-lembaga Kristen yang pernah ikut dibesarkannya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT, dan lain-lain. Ketika Parkindo berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia, kini PDI-P), Leimena diangkat menjadi anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI, dan pernah pula menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini.
Gugatan Nurani
Kepedulian pada kesehatan rakyat ini boleh jadi merupakan gugatan nurani Leimena saat melihat penderitaan rakyat selama berabad-abad dijajah. Gugatan nurani Leimena ini tergambar dalam beberapa buah buku yang ia tulis. Diantaranya, ”Membangun Kesehatan Rakjat” (Noordhoff-Kolff N.V. 1952 Djakarta), ”Kesehatan Rakjat di Indonesia” (Van Dorf 1956) dan ”Public Health in Indonesia” (Van Dorf 1956). Buku-buku tersebut adalah saksi kepedulian Leimena pada masalah kesehatan rakyat Indonesia.
Ada pula saksi hidup yang mengukuhkan keyakinan betapa perdulinya Leimena pada rakyat kecil. Nama tokoh tersebut adalah Prof DR Dr Poorwo Soedarmo (pdpersi.co.id, 31/5). Poorwo diangkat sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat (1952) oleh Leimena yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Wilopo. Alasan pengangkatan Poorwo Soedarmo ini berdasarkan laporan Organisasi Pangan Sedunia (FAO) yang menyebutkan, dari 43 negara rawan gizi, Indonesia saat itu berada pada urutan paling buntut dalam daftar konsumsi protein dan karbohidrat.
Untuk mengatasi masalah ini, Leimena kemudian membebankan tujuh tugas pada pundak Poorwo. Tujuh tugas itu: pertama, survei gizi. Kedua, sadar gizi bukan cuma masyarakat saja melainkan dokter-dokter dan pemerintah. Ketiga, perbaikan pelayanan makanan di rumah-rumah sakit. Keempat, mengajak dokter mempelajari up to date nutrition dan menyesuaikan terapi serta diagnosis. Kelima, mengembangkan dietetik. Keenam, pembentukan kader. Ketujuh, pemerintah diarahkan kepada suatu National Food Policy.
Itu hanyalah gebrakan kecil Leimena. Gebrakan lain yang cukup terasa pengaruhnya adalah saat ia mengadakan unit-unit jawatan kesehatan kuratif dan preventif yang tersusun untuk rakyat, khususnya rakyat di desa-desa (rural areas). Usaha kuratif ini meliputi, memperluas tempat-tempat orang sakit, hamil, anak-anak, baik di kota maupun daerah-daerah luar kota, serta memperbanyak jumlah balai-balai pengobatan di daerah-daerah luar kota.
Leimena menganggap, memperbanyak jumlah balai pengobatan di daerah luar kota (desa) sangat perlu dengan alasan, ketika itu di Indonesia ada 28.000 desa. Namun, tidak semua desa berekonomi kuat. Apalagi, Sumber Daya Manusia sedikit dan terbatas sifatnya. Begitu pula halnya dengan fasilitas kesehatan. "Rakyat desa tak boleh hanya dilayani dengan tindakan preventif, tapi juga usaha kuratif," tegasnya di masa itu.
Maka, mulailah usaha-usaha preventif dilakukan Leimena. Antara lain, mendirikan balai-balai nasehat kesehatan (consultatie bureaux) untuk orang hamil dan bayi, dan pemberian pendidikan kesehatan intensif bagi rakyat di desa-desa.
Sebagai percontohan, J. Leimena kemudian mencanangkan Bandung Plan. Bandung Plan ini merupakan suatu kombinasi dari usaha kuratif dan preventif yang dijalankan bersama-sama di bawah satu pimpinan dengan cara intensif. Bandung Plan berjalan cukup baik. Sehingga akhirnya, usaha percontohan Bandung Plan ditularkan ke daerah-daerah lain, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Setidaknya, upaya ini merupakan gebrakan lumayan baik bagi seorang anak bangsa. Mengingat Republik saat itu masih terlampau muda umurnya, pun dengan beragam permasalahan yang ada.
Etika Dokter
Masalah moralitas kemudian menjadi masalah yang juga teramat diperhatikan oleh J. Leimena. Moralitas yang dimaksud adalah moralitas pada para dokter. Bagi Leimena, tugas dokter merupakan tugas suci yang mesti diemban dengan sebaik-baiknya. Dokter bertugas melakukan pelayanan sosial. Namun ada masalah yang timbul setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II, yaitu semakin menurunnya tingkatan etika dari para pegawai yang bekerja di lapangan kedokteran, seperti dokter, bidan, jururawat dan sebagainya.
Hal ini tergambar pada hampir semua negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, Leimena mengusahakan agar di Indonesia tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan etika kedokteran. Ini tertulis dalam bukunya ”Dokter dan Moral” (Etika Kedokteran, Dr J. Leimena, Noordhoff-Kolff NV, 1951, Djakarta).
Gebrakan J. Leimena yang lain adalah mengatur agar tidak terjadi plus-minus dalam penempatan pegawai medis dan pegawai para-medis (ahli obat, analis, kontrolir kesehatan, bidan, jururawat, mantri hygiene dan pendidik hygiene) di nusantara. Sebagai buktinya, Leimena pernah menyatakan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Malang sebagai tempat tertutup bagi praktek baru dokter gigi dan bidan (SK MenKes RI tanggal 15 Agustus 1951). Hal ini pun berlaku bagi para dokter yang akan membuka praktek di Makassar tahun 1951. Menurut Leimena, jumlah dokter di Makassar terlampau banyak dibandingkan tempat-tempat lain di Indonesia, maka ia menyatakan Makassar sebagai tertutup untuk menjalankan praktek baru bagi dokter (SK Menkes RI tanggal 18 Oktober 1951).
Tak dapat dipungkiri, J. Leimena adalah sosok multidimensial. Mungkin tiada yang tahu apa yang ada dalam benaknya; berkarier di dunia politik untuk mendukung kemajuan dunia kesehatan Indonesia, ataukah gebrakannya di dunia kesehatan untuk menunjang karier politiknya. Walau demikian, apa yang telah dilakukan J. Leimena tercatat sebagai sesuatu yang besar. J. Leimena telah berbuat, dan sejarah negeri ini mencatatnya dengan tinta emas. Terutama, apa yang telah dia perbuat bagi kesehatan rakyat kecil, rakyat desa, rakyat terbesar yang dimiliki negeri ini, negeri Indonesia.
Gelar pahlawan
Konsistensi dan kesetiaan Leimena terutama pada ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh hingga akhir hayatnya. Kesetiaan Leimena terhadap sahabatnya, Soekarno, telah teruji pascatragedi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Ketika semua orang menjauhi Soekarno, Leimena-lah satu-satunya orang yang mendampingi Proklamator itu di Istana Bogor.
Salah satu pemikiran penting Leimena bagi nasionalisme umat Kristen Indonesia, yang digarisbawahi Seto Harianto, adalah dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan bagi Tanah Air, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, ia mengingatkan, orang Kristen tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai pencinta Tanah Air. Orang Kristen juga harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis sejati.
Biodata J. Leimena
Nama lengkap : Johannes Leimena
Nama panggilan : Om Jo
Tempat / Tanggal lahir : Ambon / 06 Maret 1905
Riwayat Pendidikan :
SR di Ambon
Europeesch Lagere School/ELS (hanya beberapa bulan saja)
Sekolah Menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang)
MULO Kristen
Pendidikan Kedokteran di STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen), Surabaya (1930)
Geneeskunde Hogeschool/GHS (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta (1939)
Riwayat Organisasi :
Motor Zendingsconsulaat Batavia dalam mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di BandungTahun 1926
Motor Jong Ambon dalam mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928
Pendiri CSV (sekarang GMKI)
Salah Satu Pendiri Parkindo Tahun 1945 dan merupakan Ketua Umum Periode 1950-1957
Salah Satu Pendiri Dewan Gereja Indonesia (kini PGI) pada Tahun 1950 dan Menjabat sebagai Wakil Ketua yang membidangi Komisi Gereja dan Negara
Riwayat Karir :
Menteri Muda Kesehatan Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946)
Wakil Menteri Kesehatan Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)
Menteri Kesehatan Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947)
Menteri Kesehatan Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948)
Menteri Kesehatan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
Menteri Negara Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)
Menteri Kesehatan Kabinet Republik Indonesia Serikat/RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
Menteri Kesehatan Kabinet Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951)
Menteri Kesehatan Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952)
Menteri Kesehatan Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)
Menteri Kesehatan Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)
Menteri Sosial Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)
Menteri Distribusi Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960)
Wakil Menteri Utama merangkap Menteri Distribusi Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962)
Wakil Menteri Pertama I Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 Desember 1963)
Wakil Perdana Menteri II Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964)
Menteri Koordinator Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964-22 Februari 1966)
Wakil Perdana Menteri II merangkap Menteri Koordinator, dan Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 - 28 Maret 1966)
Wakil Perdana Menteri untuk urusan Umum Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966 - 25 Juli 1966)
PERIODEISASI GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1950. Namun Christelijke Studenten Vereeniging op Java (CSV) yang menjadi cikal bakal GMKI telah ada jauh sebelumnya dan berdiri sejak 28 Desember 1932 di Kaliurang.Adapun secara ringkas periodisasi sejarah GMKI adalah :
CSV Op Java ( 1932 – 1942 )
PMKI ( 1945 – 1950 ) dan CSV Baru ( 1946 – 1950 )
GMKI ( 1950 sampai sekarang )
C.1. CSV Op Java
Tokoh yang tidak dapat dilupakan perannya dalam kelahiran CSV OP java adalah aktivis WSCF Ir. C. L. Van Doorn. Beliau adalah seorang sarjana kehutanan yang aktif mempelajari ilmu-ilmu sosial dan ekonomi pertanian. Bahkan sampai ajalnya ia juga memperoleh gelar Dominee dalam bidang theologia. C.L Van Doorn tiba di Batavia tahun 1921, Ketika itu dia belum memahami karakter, budaya dan situasi bangsa Indonesia saat itu, sehingga ia memutuskan belajar untuk memahaminya dengan bekerja dikantor Volksrediet Purworejo.
Munculnya mahasiswa di Indonesia seiring dengan berdirinya Perguruan Tinggi yang ada dipulau Jawa diantaranya adalah School Tot Opleiding Van Indische Artsen ( STOVIA ) di Batavia tahun 1910-1924, Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1920, Sekolah Tinggi Hewan di Bogor tahun 1914 dan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta tahun 1924. Pada tahun 1924 terbentuklah Batavia CSV di Batavia yang merupakan CSV pertama yang ada, kemudian mahasiswa yang ada di Surabaya dalam kurun waktu 1935-1927 berkumpul dan membentuk Jong indie. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kedua kelompok ini adalah Penelahan Alkitab dan Kelompok kecil dan diskusi seputar kehidupan sosial yang ada secara aktif dan intens.
Pada bulan Desember 1932 ketika orang Kristen sedang merayakan natal, kelompok-kelompok ini mengadakan konperensi di Kalirung dan hasilnya dibentuklah Christelijke Studenteen Vereeniging Op java (CSV Op Java) pada tanggal 28 Desembar 2932 dan saat itu dipilih Dr. J. Liemena sebagai ketua dan Ir. C.L Van Doorn sebagai sekretaris.
Peristiwa lain yang tidak kalah penting yang mempengaruhi CSV Op Java ialah kehadiran Dr. John R. Mott pada tahun 1926, beliau merupakan tokoh pendiri dari World Student Cristian Federation yang didirikan pada tahun 1885 di Swedia. Kehadirannya di Indonesia merupakan tonggak sejarah bagi kelahiran CSV Op Java dimana berkat bantuannya CSV Op Java diberi kepercayaan oleh WSCF untuk menjadi tuan rumah penyelenggraan Konprensi GMK-GMK se-Asia pada tahun 1933 di Citeureup, Jawa Barat. Pada saat konperensi ini CSV Op Java diterima menjadi Corrresponding Member dari WSCF, dimana keanggotaan WSCF ada 3 yaitu :
Pioneering Movement
Corresponding Movement
Affiliated Movement (Full Member)
Jumlah anggota pada era 1930an sekitar 90 orang yang tersebar di kota-kota yang baru ada Perguruan Tingginya. Sekalipun kecil dan lemah namun CSV Op Java telah berhasil meletakkan dasar pembinaan kepada mahasiswa Kristen di Indonesia yang selanjutnya dilanjutkan oleh GMKI. Ada dua aspek yang merupakan benang biru yang dilahirkan oleh CSV Op Java yaitu kerjasama GMK -GMK se-Asia (oikumenisme) dan rasa semangat persatuan nasional (nasionalisme)
Masa eksistensi CSV Op Java berakhir ketika jepang masuk ke Indonesia. Dengan itu, maka semua organisasi-organisasi bentukan Belanda dibubarkan dan dilarang untuk beraktifitas. Maka pada tahun 1942 CSV Op Java praktis tidak ada lagi dan tidak beraktifitas lagi.
C.2. PMKI dan CSV baru (Masa Revolusi Kemerdekaan RI 1945)
Dalam suatu pertemuan pada tahun 1945 di STT Jakarta, mahasiswa-mahasiswa Kristen saat itu membentuk organisasi mahasiswa Kristen yang dimaksud untuk menggantikan CSV Op Java yang bernama Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI). Saat itu Dr. J. Leimana ditetapkan sebagai ketua dan Dr. O. E. Engelen sebagai sekretaris.
Kegiatan yang dilakukan PMKI tidak terlalu berbeda dengan yang dilakukan oleh CSV Op Java, Penelahaan Alkitab dalam kelompok-kelompok kecil merupakan kegiatan utamanya disamping studi-studi tentang kondisi nasional dan ideologi bangsa saat itu. Tidak lama setelah lahirnya PMKI, diawal tahun 1946 muncul suatu organisasi baru yang bernama CSV. CSV baru sebenarnya bukanlah tandingan dari PMKI hanya CSV ini lebih berorientasi kepada “Pemerintahan pendudukan Belanda“ sehingga dalam gerakan dan aktifitasnya sering terjadi pertentangan-pertentangan. Ditengah pertentangan-pertentangan dan problemalatikanya masing-masing, maka ada dua kesamaan diantara kedua organisasi ini, yaitu sama-sama berusaha dan berjuang untuk :
Perealisasi Iman dalam Yesus Kristus sebagai sebuah persekutuan
Menjadi saksi Kristus dalam dunia mahasiswa
C.3. GMKI yang melanjutkan Misi dan Eksistensinya
Menurut Tarianto, BA pada masa keberadaan GMKI dibagi menjadi :
(a). Masa Perkembangan (1950-1960)
Dengan berakhirnya pertentangan antara Indonesia dan Belanda maka berakhir pula pertentangan antara PMKI dan CSV pada akhir tahun 1949. Puncak dari akhir pertentangan tersebut ialah pada saat pertemuan di Jl Teuku Umar 36 Jakarta (rumah Dr J. Leimena) tanggal 9 Februari 1950. Wakil-wakil dari kedua organisasi tersebut sepakat untuk meleburkan diri dan bergabung bersama dengan nama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Sebuah catatan sejarah yang sangat tinggi nilainya bagi gereja dan negara saat proses proklamasi kehadiran GMKI dipilihlah Dr J. Leimena sebagai ketua sementara sampai diadakannya Kongres yang pertama dan pada kesempatan itu Leimena berpidatao yang diantaranya berbunyi :
“Tindakan ini adalah tindakan historis bagi dunia mahasiswa umumnya dan masyarakat Kristen Khususnya. GMKI menjadi pelopor semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakkan di Indonesia. GMKI menjadilah pusat, sekolah latihan (Leader School) dari orang-orang yang mau bertanggungjawab atas segala sesuatu mengenai kepentingan dan kebaikan bangsa Indonesia. Persekutuan dalam Kritus Tuhannya. Dengan demikian ia berakar baik dalam gereja, maupun dalam nusa dan bangsa Indonesia, sebagai bagian dalam iman dan roh, ia berdiri dalam dua Proklamasi : Proklamasi kemerdekaan dan Proklamasi Tuhan Yesus dengan Injilnya, yaitu Injil kehidupan, kematian, dan kebangkitan."
Mulai dari sana GMKI melanjutkan perjuangan dan pengembangan organisasinya dengan melakukan kongres dan melakukan pengembangan cabang-cabang. Pada tahun 1953 GMKI Cabang Medan dibentuk bersama-sama dengan Cabang Bogor dan pada tahun itu pula melalui General Assembly WSCF di Nasrapur India, GMKI resmi diterima sebagai affiliated Movement (Full Member) WSCF. Periode awal ini sampai 1960 disebut sebagai fase perkembangan organisasi dengan mengadakan pembentukan cabang-cabang baru.
(b). Masa Konsolidasi (1960-1970)
Pada era ini terjadi suatu pergolakan Nasional yang pokok persoalannya ialah masalah Struktur negara dan kepemimpinan nasional. Sikap yang diambil oleh Pengurus Pusat GMKI terkesan lamban karena wacana yang ada pada Pengurus Pusat pada saat itu yaitu pergantian atau pergerseran Soekarno sebagai Presiden belum bisa dilakukan tanpa pergeseran Pancasila dan UUD 1945. Setelah terjadi kesepakatan untuk tidak terjadi pergeseran Pancasila dan UUD 1945 barulah GMKI menyetujui pembubaran PPMI dan menyetujui pembentukan KAMI. Melihat kelambanan Pengurus Pusat, maka pada saat itu banyak anggota GMKI yang melakukan protes dengan melakukan aksi coret-coret menuntut percepatan sikap Pengurus Pusat GMKI. Kelambanan Pengurus Pusat GMKI saat itu, sedikit banyaknya telah mempengaruhi cabang-cabangnya dalam mengambil langkah, namun untuk cabang Medan Aktifis GMKI Medan saat itu ikut berperan Aktif di KAMI bahkan menjadi Garda depan dari pergerakan mahasiswa saat itu.
Pada era ini GMKI dengan dinamika internalnya disibukkan untuk melakukan konsolidasi organisasi dimana terjadi pertentangan antara Pengurus Pusat GMKI dan cabang-cabang saat itu. Oleh karena itu, maka dari kongres ke kongres terjadi perubahan-perubahan dalam diri GMKI diantaranya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga GMKI yang mengatur tentang perubahan tata organisasi GMKI dari yang desentralisasi menjadi sentralisasi.
(c). Masa Pengutusan
Setelah Soeharto menggantikan Soekarno dengan pemerintahan Orde barunya, maka saat itu bulan madu antara militer dan mahasiswa yang sebelumnya terjadi, berakhir. Hal ini tampak dengan pembubaran KAMI. Melihat hal tersebut, maka organisasi mahasiswa Ekstra kampus, yaitu HMI, GMKI, PMKRI, PMII, GMNI mengadakan pertemuan di Cipayung pada tanggal 22 Januari 1972 dan melakukan penandatanganan kesepakatan yang dikenal dengan nama Kesepakatan Cipayung dan kelak ke-lima organisasi ini disebut dengan Kelompok Cipayung dimana tema yang diambil pada pertemuan kelompok ini adalah “Indonesia yang dicita-citakan“. Kelompok Cipayung ini adalah kelompok yang sifatnya informal dan tidak mempunyai struktur dan tata organisasi lainnya.
Pada tanggal 23 Juli 1973 Kelompok Cipayung memprakarsai pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang merupakan organisasi gabungan kepemudaan yang mempunyai tujuan untuk melibatkan pemuda berperan serta dalam pembangunan nasional dan juga untuk menghindarkan pengkotak-kotakan semu antara pemuda. Akhir tahun 1970-an ketika Daeod Joesoef mengeluarkan NKK/BKK yang melarang organisasi ekstra untuk melakukan segala macam aktifitas didalam kampus dan juga pembubaran Dewan Mahasiswa, maka ini sangat mempengaruhi GMKI dalam melakukan pembinaan dan pengkonsolidasian kepada anggotanya, dimana sebelumnya pembinaan kepada anggota GMKI dilakukan langsung di dalam kampus. Sejak itu timbul ide dan Strategi yang dipakai GMKI dengan membentuk KMK Atau PMK yang diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan GMKI dalam melakukan pembinaan anggota dalam kampus. Namun seiring waktu berlalu, strategi ini seolah-olah bukan lagi Strategi GMKI. Mungkin ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman Theologia.
Disaat era 90-an kekritisan organisasi ekstra mulai dipertanyakan secara lembaga, mungkin ini disebabkan oleh suatu sistem organisasi yang mapan atau birokarasi Organisasi yang sangat panjang dalam mengambil sikap. Kader-kader GMKI dan organisasi lainnya berfungsi langsung sebagai kontrol sosial dan kekuasaan. Sampai saat jatuhnya Soeharto peran organisasi ekstra, khususnya GMKI tidak nyata secara lembaga tetapi banyak kader-kader GMKI yang cukup aktif sebagai penggerak dalam pergerakan mahasiswa saat itu.
Memasuki era pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati yang kita sebut sebagai era reformasi, GMKI mencoba untuk eksis menjadi organisasi kader dan organisasi mahasiwa sebagai kontrol pemerintah dan kontrol sosial walaupun dalam aksinya kita analisa kembali sejauh mana peran dan kekritisan yang diambil oleh GMKI dalam melakukan perannya terasebut.
B.4. Perkembangan GMKI
Saat ini, GMKI memiliki 65 cabang yang tersebar di kota-kota perguruan tinggi di berbagai provinsi di Indonesia. GMKI merupakan tempat persiapan kader dengan kompetensi dalam iman, ilmu, kepemimpinan dan kepekaan sosial yang dapat diaplikasikan dalam tiga medan pelayanannya yakni, gereja, perguruan tinggi dan masyarakat.
Dalam melakukan Pelayanannya, GMKI membangun kerjasama dengan beberapa institusi seperti Gereja, Universitas, LSM, MEDIA, aktif dalam Kelompok Cipayung (GMKI, GMNI, PMKRI, HMI, PMII) dan FKPI (Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia) dengan berbagai program kerjasama. GMKI juga berafiliasi dengan Federasi Mahasiswa Kristen se-Dunia (WSCF) dan saat ini membangun jaringan dengan Perkumpulan Organisasi Kristen dalam bidang Sosial se-Asia (ACISCA).
Compiled by : Henry Nainggolan
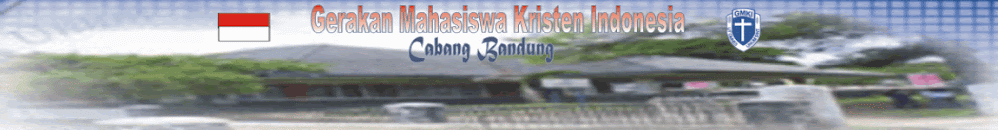






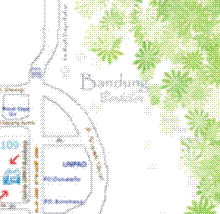



0 komentar:
Posting Komentar